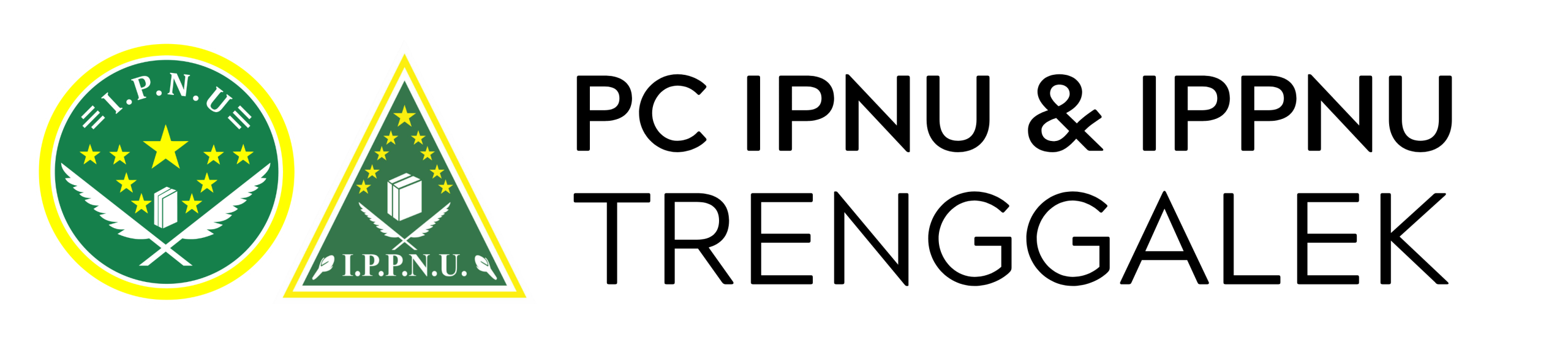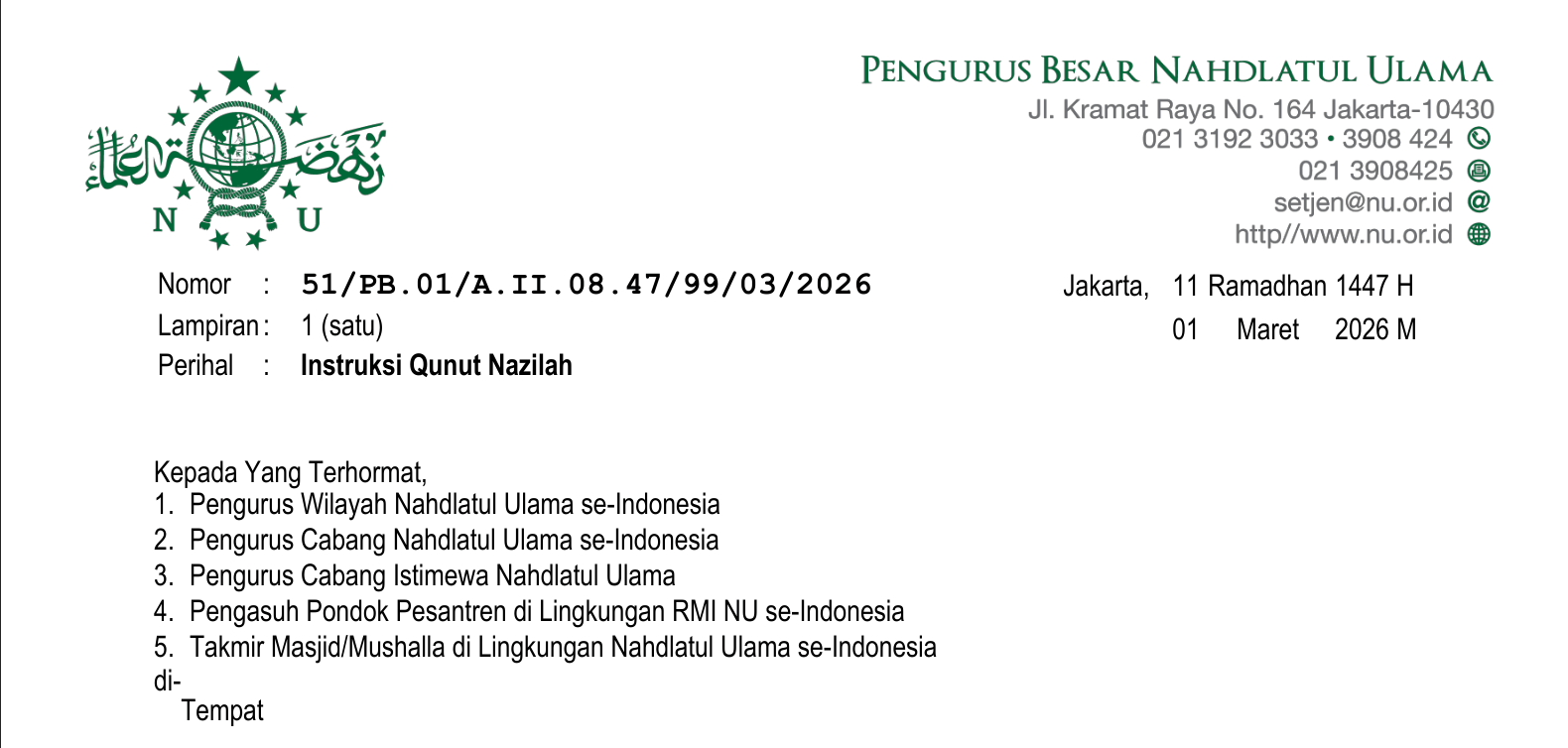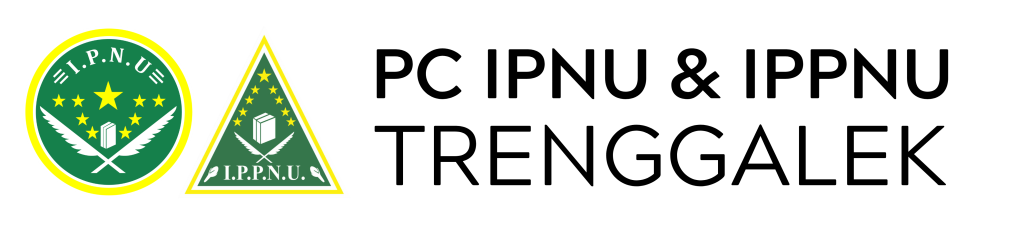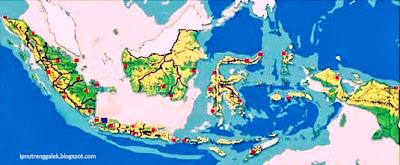
Sejarah selalu berulang. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ’65 selain sejarah itu sendiri dan kepentingan rekonsiliasi? Bagaimana menempatkan, sekaligus mengambil pelajaran, dari kasus ’65 dalam konteks konflik sumber daya alam (SDA) di Indonesia masa kini dan yang akan datang? Tulisan ini melihat beberapa kemiripan diantara keduanya, dan bertolak dari situ tulisan ini merumuskan agenda gerakan.
Asia Tenggara 1930-60
Dalam buku Moral Economy of Peasant Rebellion in South East Asia (Scott, 1976) disebutkan bahwa pada tahun 1930-an terjadi beberapa pemberontakan petani di Asia Tenggara seperti di Vietnam, Burma, Indonesia, dan Filipina (yang sekarang). Prakondisi sosial-ekonomi yang melatarbelakangi pemberontakan petani adalah kolonialisasi dan krisis ekonomi di tahun 1930-an yang diikuti oleh kenaikan pajak yang dikenakan kepada para petani.
Beberapa dekade kemudian kaum pergerakan di masing-masing daerah di Asia Tenggara tersebut menemukan formula nasionalisme sebagai antitesis terhadap kolonialisme, sekaligus mencoba menjawab eksploitasi yang nyaris tanpa batas oleh penjarah di kawasan ini. Indonesia sendiri merdeka sekitar satu setengah dekade setelahnya.
Pasca kemerdekaan di tahun 1945, di bawah Soekarno, Republik Indonesia (RI) melakukan gerakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1957-59. Politik nasionalisasi ini berhasil memindahtangankan kepemilikian 90% perkebunan ke tangan pemerintah RI, 62% nilai perdagangan luar negeri, dan sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, bank, perkapalan, dan sektor jasa (Kanumoyoso, 2001).
Zaman terus bergulir, pada tahun 1965, dalam kondisi perang dingin yang semakin memanas, melalui sebuah kudeta yang merangkak, Soekarno didongkel dari kursi kepresidenan dan diganti oleh Jenderal Soeharto yang disokong penuh oleh kekuatan global, Amerika Serikat (Klein, 2008). Dan sejak saat itulah secara perlahan kekuatan kapital internasional mencengkeramkan kuku-kukunya untuk menjarah hampir seluruh penjuru negeri, sampai sekarang.
Peristiwa ’65 telah menyebabkan hilangnya pekerja-pekerja kebudayaan terbaik di masanya, dan karena lazimnya dalam semua peradaban bahwa para pekerja kebudayaan adalah para penantang terdepan setiap bentuk eksploitasi dan fasisme, maka kemusnahan mereka secara massal telah memuluskan rezim birokratik-militeristik otoriter Orde Baru untuk berkuasa penuh selama 32 tahun (Supartono, 2000) dengan cara menumpuk hutang luar negeri dan melego kekayaan alam.
Konflik SDA di Indonesia pada tahun 2013
Konflik di bidang SDA adalah salah satu permasalahan besar di Indonesia pasca reformasi. Sepanjang tahun 2013 yang masih berlangsung saja telah terjadi 232 konflik SDA di 98 kabupaten kota di 22 provinsi yang diiring dengan jatuhnya korban sebagain besar dari kalangan kaum tani. Dari sebanyak 232 konflik SDA yang melibatkan petani ini, 69% di antaranya dengan korporasi (swasta), Perhutani 13%, taman nasional 9%, pemerintah daerah 3%, instansi lain 1% (Kompas, 16/02/2013), dan sisa 5% lainnya tidak dijelaskan oleh Kompas.
Kemiripan ’65 dan Pasca-Reformasi
Ada beberapa kemiripan antara apa yang terjadi dalam periode 1930-60-an dengan apa yang terjadi di Indonesia sejak Reformasi 1998 sampai sekarang.
Kemiripan pertama, tengah terjadi perubahan yang mendasar dalam hal tata kelola kenegaraan. Pada kurun 1930-60, gelombang nasionalisme telah meruntuhkan penjajahan yang telah bercokol selama berabad-abad. Kemerdekaan datang, maka berubahlah sistem kolonial menjadi negara-bangsa. Masa pergerakan dan transisi menuju kemerdekaan ini rupanya, seperti yang sudah disampaikan di atas, sampai memengaruhi kehidupan kaum tani dalam hal pajak yang meningkat di zaman kolonial.
Pasca-Reformasi 1998; disadari atau tidak, sedang terjadi juga perubahan besar-besaran dalam hal tata kelola bernegara di Indonesia. Tonggak-tonggak yang paling dapat dilihat adalah desentralisasi yang memberikan kekuasaan lebih besar terhadap pemerintah kabupaten/kota. Akan tetapi, hal yang jarang disadari adalah bahwa konfigurasi triad lama “negara-korporasi-masyarakat” secara perlahan juga mulai berubah menjadi “korporasi+negara-masyarakat”. Negara Orde Baru yang otoriter telah tumbang berganti dengan Negara Pasca-Reformasi yang menjadi perpanjangan tangan kapital.
Ada beberapa fakta pendukung untuk lahirnya konfigurasi baru ini. Hukum yang tadinya berfungsi untuk melayani warga negara dan melindunginya dari tindakan kesewenang-wenangan yang mungkin terjadi, telah berubah menjadi instrumen yang menyukseskan peneterasi kapital lebih dalam di sektor ekstraksi.
Contoh pertama lahir dari kasus Lumpur Lapindo. Pada Agustus 2009, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan perkara (SP3) yang membuat penyelidikan terhadap kasus Lumpur Lapindo tidak bisa diproses lebih lanjut di pengadilan (Batubara, 2011). Keluarnya SP3 ini menafikan analisis yang menyatakan bahwa bencana Lumpur Lapindo terjadi karena selubung pengeboran di sumur Banjar Panji-1 (BJP-1) dipasang lebih pendek dari yang direncanakan (Tingay et al. 2008; Batubara dan Utomo, 2012; Batubara 2013), dan dengan demikian, ia adalah sebuah bencana industri, alias kejahatan korporasi.
Contoh kedua datang dari kasus ekspansi PT Semen Gresik (SG) ke Pegunungan Kendeng Utara (PKU) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati dicoba disesuaikan dengan kepentingan ekspansi PT SG. Kawasan PKU yang dalam RTRW 1993-2012 Kabupaten Pati, masuk dalam kawasan pertanian dan pariwisata, mau diubah peruntukannya menjadi kawasan industri dan pertambangan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029. Di sini kita melihat bahwa dokumen RTRW justru mau “disesuaikan”untuk kepentingan ekspnasi PT SG ke PKU di Kabupaten Pati (Batubara, dkk. 2010).
Contoh ketiga adalah kemenangan korporasi dalam kasus uji materiil kasus Lumpur Lapindo dan Sorikmas Mining di Mahkamah Agung (Batubara, 2012).
Dari ketiga contoh di atas, tak ada jalan lain, seseorang harus menyimpulkan bahwa di bidang hukum, isu sudah bergerak dari “tidak adanya penegakan hukum” ke “hukum yang sudah ditunggangi oleh kepentingan ekspansi kapital dan pada saat yang bersamaan mengabaikan kepentingan masyarakat.” Lebih lanjut, negara sudah tidak lagi berfungsi sebagai regulator dalam formasi konvensional triad “negara-korporasi-masyarakat”, tetapi sudah berubah menjadi kacung dalam formasi yang sedang menjadi “korporasi+negara-masyarakat”.
Artinya, untuk melihat kemiripan dengan peristiwa sejarah di tahun 1930-60-an, sekarang ini sedang terjadi perubahan tata kelola kenegaraan kita dari negara Orde Baru yang sentralistik dan sangat kuat, menjadi negara Pasca-Reformasi yang terdesentralisasi dan secara perlahan berubah menjadi perpanjangan tangan kapital. Dan ini, rupanya, menyenggol juga kepentingan kaum tani sehingga memicu munculnya 232 konflik SDA di tahun 2013 yang masih berjalan dengan mayoritas di antaranya (65%) adalah konflik petani versus korporasi(+negara).
Kemiripan kedua adalah menguatnya politik nasionalis. Pada zaman 1930-60-an hal ini ditandai dengan keberhasilan kaum pergerakan kemerdekaan memformulasikan permasalahan mereka di dalam konsep nasionalisme dan dengan itulah mereka keluar dari kungkungan kolonial.
Kemenangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi kepala daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) adalah salah satu bukti dari penguatan kelompok nasionalis. Jokowi yang sebelumnya merangkak dari bahwa sebagai pengusaha mebel, menjadi Walikota Solo, dan seterusnya Gubernur DKI, memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi presiden RI pada pemilu 2014 mendatang. Prediksi ini didukung oleh tingkat keterpilihan Jokowi sebagai calon presiden yang sangat tinggi dari berbagai penelitian yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei dan menjadi berita di berbagai media.
Kenaikan Jokowi menjadi tonggak menguatnya ideologi nasionalisme yang bahkan pada era Megawati Soekarnoputri pun kehilangan artikulasinya. Alih-alih melakukan politik nasionalisasi seperti halnya Soekarno pada tahun 1957-59 seperti yang disinggung di atas, Megawati malah melakukan hal sebaliknya dengan melego sejumlah BUMN ke pasar internasional. Sebaliknya, Jokowi, meskipun baru saja naik menjadi Gubernur DKI, langsung mencoba menemukan kembali artikulasi ideologi nasionalisme melalui usahanya untuk mengambil alih perusahaan minum yang melayani masyarakat di DKI, Palyja, dari tangan investor internasional yang berasal dari Perancis (Hidayat, 2013).
Kalau Jokowi berhasil dengan percobaannya mengambil alih Palyja di DKI, maka ekstrapolasi yang akan keluar adalah: Jokowi akan menjadi Presiden RI pada tahun 2014, dan akan memulai politik nasionalisasi perusahaan asing yang lebih luas, atau setidaknya ia akan terus-menerus mencoba mengartikulasikan kembali ideologi nasionalisme dalam ranah ekonomi-politik.
Skenario ini mengantarkan kita pada kenyataan bahwa kapital nasional dan internasional pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan bergerak memobilisasi segala sumber daya yang mereka miliki untuk menjaga kepentingan ekstraksinya di Indonesia. Dan, di titik ini, kasus ’65 bukan lagi sejarah, tetapi ia adalah hal yang di depan mata.
Kemiripan ketiga; dalam diskursus mengenai ’65 yang berkembang, kalangan Nahdliyin terlibat sangat jauh sebagai mesin penjagal kelompok Partai Komunis Indonesia (PKI) ataupun kelompok yang berafiliasi (secara struktural dan idelogis) dengannya. Tetapi cara pandang lain bisa juga ditampilkan, bahwa Nahdliyin juga adalah korban dari peristiwa ini karena pada kenyataannya, bukan tidak ada korban ’65 dari kalangan santri. Lebih jauh, Nahdliyin sebagian besar pada waktu itu adalah dari kalangan petani pedesaan dengan tingkat kemelekan yang rendah. Dan dengan demikian, agenda riset yang harus dirangsang di titik ini adalah melihat kalangan Nahdliyin sebagai korban skenario politik kalangan yang lebih melek yang mengambil untung dari peristiwa ’65.
Pola yang sama sudah memperlihat bentuknya dalam berbagai konflik SDA di basis Nahdlatul Ulama (NU). Kita dapat melihat beberapa kasus seperti konflik pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Batang, kasus konflik rencana pembangunan pabrik semen di PKU Kabupaten Pati, konflik tambang pasir besi Urutsewu di Kebumen Selatan, dan konflik bahan galian C di Kabupaten Mojokerto (FN-KSDA, 2013). Dalam semua kasus yang disebutkan di atas, pola yang terjadi adalah perbedaan aspirasi (kepentingan) antara elit NU dengan kelompok akar rumput yang sebagian besar adalah petani. Di satu sisi, elit NU merestui ekspansi kapital dan, dalam beberapa kasus, bahkan menjadi bagian dari proses ekspansi kapital itu sendiri dengan jalan mengambil posisi perantara; di sisi lain kelompok akar rumput bergerak menolak ekspansi kapital di bidang industri ekstraktif ini karena mereka merasa penghidupannya terganggu. Pola seperti ini juga ditemukan dalam kasus tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi. Bahkan lebih jauh, dalam kasus eksplorasi beberapa perusahaan minyak dan gas (migas) di Madura, Kiai bahkan mengambil posisi memuluskan jalan perusahaan migas untuk membebaskan lahan dan memastikan proses eksplorasi tidak mengalami gangguan. Tak pelak, hal ini kemudian memunculkan istilah “Kiai Migas” di Madura (Hakim, 2010).
Untuk melihat kemiripan dengan kasus ’65, maka dalam kasus konflik SDA sekarang seperti yang sudah diuraikan dalam pragraf sebelumnya, yang bisa kita lihat adalah polarisasi kepentingan di kalangan NU sendiri yang (kira-kira) mengerucut ke konflik elit vs akar rumpur di kalangan santri. Kalau skenario politik nasional di atas berjalan, dalam artian Jokowi naik menjadi presiden di 2014 dan ia konsisten dengan artikulasi ideologi nasionalismenya yan kemudian disusul dengan bergeraknya kekuatan kapital di sektor ekstraktif untuk mengamankan asetnya, maka, kasus ’65 bukan sebuah sejarah masa lalu, tetapi kita harus sudah siap menghadapinya. Karena, tinggal dibutuhkan satu gerakan yang secara aktif melakukan ideologisasi untuk memperruncing friksi elit vs akar rumput di kalangan santri, maka konflik berdarah akan terulang. Ini artinya, kelompok petani-santri di pedesaan akan kembali menjadi korban.
Gus Dur dan SDA
Apa yang bisa diambil dari Gus Dur dalam hal tata kelola SDA di Indonesia? Gus Dur adalah seorang nasionalis tulen. Dalam sebuah orasi di hadapan massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Malang, sehubungan dengan SDA, Gus Dur menyatakan bahwa “Ada tiga macam sumber alam, itu harus direbut kembali, dipakai untuk memakmurkan Bangsa kita…Satu, sumber hutan; kedua, sumber pertambangan dalam negeri; tiga, sumber kekayaan laut (Gus Dur, –).”
Pesan di atas sebenarnya terartikulasikan dalam sikap yang lebih konkrit dalam kasus pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Jepara, ketika Gus Dur mengancam akan mogok makan apabila PLTN didirikan di Jepara. Pernyataan ini kemudian memobilisasi kantong-kantong NU untuk mengadakan perlawanan yang lebih masif menolak pendirian PLTN di Jepara (Fauzan dan Schiller, 2011).
Dalam kontestasi terhadap akses dan kontrol terhadap sumber daya yang lebih sengit dalam kasus Lumpur Lapindo, Gus Dur meminta kepada salah satu kiai rakyat agar tidak menjual tanah mereka. Kelompok ini kemudian yang mengambil sikap paling radikal dalam kasus Lumpur Lapindo dengan memilih tidak menjual tanahnya kepada PT Minarak Lapindo Jaya, kasir PT Lapindo Brantas Inc., seperti yang diperintahkan oleh Peraturan Presiden 14/2007 (Batubara, 2010).
Terhadap gerakan petani internasional yang menyuarakan kedaulatan petani seperti organisasi petani se-dunia, La Via Campesina, Gus Dur sangat respek terhadap usaha para petani membangun gerakan alternatif terhadap penetrasi lembaga keungan dunia seperti International Monetary Fund (IMF) yang sangat merugikan petani (–, 2006).
Dari beberapa nukilan sikap Gus Dur di atas, artikulasinya jelas tanpa tedeng aling-aling. Gus Dur berdiri di belakang Soekarno dalam hal tata kelola SDA.
Agenda Gerakan
Dari penjelasan di atas, maka Nahdliyin tidak punya pilihan lain kecuali: bergerak. Miskinnya kotribusi Lesbumi dalam teks ’65 disebabkan oleh dua hal. Pertama, Lesbumi tidak terlalu aktif pada zaman itu. Kedua, pada zaman sekarang riset dengan mengambil kontribusi Lesbumi dalam kasus ’65 tidak terlalu banyak. Kedua argumen di atas pada dasarnya berujung pada satu titik yang sama: kelompok Lesbumi tidak secara aktif bergerak. Analisis ini sangat masuk akal, karena, kalau kita lihat dokumen Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), pembukaannya disebut dengan “Muqaddimah”. Artinya, dari pemilihan kata “Muqaddimah”, secara logis sebenarnya lebih mudah “menarik” Lekra untuk bergabung dengan kalangan agama (santri), daripada untuk menariknya merapat ke kalangan komunis. Secara imajinatif, andai ia adalah “Manifesto”, maka secara logis akan lebih mudah menariknya bergabung dengan PKI. Tetapi, karena kerja pengorganisasian dan pergerakan yang tidak jalan, Lesbumi dan Lekra kemudian menjadi sangat jauh, dan justru sebaliknya, Lekra semakin dekat dengan PKI. Artinya, pengalaman ’65 yang memperlihatkan secara telanjang kurangnya pergerakan di kalangan santri, seharusnya tidak boleh terulang lagi.
Dengan demikian, agenda gerakan yang paling mendesak adalah pengarusutamaan isu konflik SDA di kalangan santri. Pengarusutamaan akan membuat kalangan santri melek dengan persoalan ini, dan dengan itu diharapkan akan meminimalisir friksi kepentingan antara elit dengan akar rumput.
Pengarusutamaan tidak boleh terpenjara di kalangan santri belaka, tetapi harus menjangkau kalangan yang lebih luas seperti kelompok “nasionalis” yang lain. Untuk kelompok nasionalis isu ini sebenarnya bukan isu yang baru, yang belum dilakukan adalah keluar dari skema korporasi dan negara predatoris yang sudah menjadi perpanjangan tangan korporasi serta membangun sebuah anjungan yang dari situ agenda gerakan bersama didifusikan.
Keluar dari skema korporasi bukanlah hal yang mudah, meski tentu saja ia bukan hal yang mustahil untuk dikerjakan. Kebangkrutan sistem korporasi datang dari dalam dirinya sendiri karena terlalu ekstraktif dalam memasilitasi akumulasi kapital pada satu atau sekelompok kaum kapitalis. Kapitalisme di sini, mengikut substansi yang disampaikan Marx (1982) mengambil pengertian yang paling mendasar sebagai proses yang melibatkan “uang yang bergerak” (money in motion) dimana orang membeli bukan untuk mengonsumsi, tetapi untuk menjual kembali agar mendapatkan nilai lebih dari sebuah komoditas. Korporasi, melalui eksploitasi terhadap SDA dan perkerjanya sendiri untuk mendapatkan nilai lebih komoditas, telah menjalankan pola ini selama berpuluh-puluh tahun. Ekstraksi SDA pada dasarnya adalah sebuah proses yang menceraikan para petani dari akses dan kontrol terhadap SDA seperti tanah. Proses ini, dalam kajian kontemporer, lazim disebut sebagai “akumulasi lewat jalan perampasan”, accumulation by dispossession (Harvey, 2003).
Kalau pada zaman pergerakan kemerdekaan RI, para kaum pergerakan telah menemukan rumus gerakan dalam bentuk nasionalisme sebagai antitesis terhadap kolonialisme yang menjadi struktur tata kelola pada waktu itu, maka Pasca-Reformasi, kita dapat mengajukan “kooperasi” sebagai antitesis terhadap “korporasi” yang melakukan akumulasi kapital dengan jalan merampas akses dan kontrol SDA dari tangan-tangan pemiliknya yang sah: petani. Kedaulatan petani dalam tata kelola SDA di sini diartikan sebagai kemerdekaan penuh di pihak petani untuk menentukan secara politik tata kelola yang layak bagi SDA yang mereka miliki.
Mengapa “kooperasi”? Pertama, kita mulai dari terminologi. Dalam Bahasa Indonesia, “kooperasi” berarti “bekerjasama”, sedangkan “koperasi” berarti “perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah”. Terma “kooperasi” secara sadar dipilih sebagai antitesis terhadap “koperasi” karena tiga alasan: (1) Dalam konteks Orde Baru, lembaga-lembaga koperasi sudah dikooptasi oleh rezim birokratik-militeristik otoriter, koperasi tidak lagi menjadi lembaga yang melayani anggotanya, tetapi menjadi lembaga ekonomi tempat korupsi bersimaharajalela sekaligus menjadi mesin ideologisasi Negara Orde Baru; (2) Pasca-Reformasi, Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian membonsai “kooperasi” menjadi lembaga ekonomi semata dengan membaginya menjadi koperasi produsen, konsumen jasa, dan simpan pinjam. Pembonsaian ini menyebabkan koperasi kehilangan semangat gerakannya, menyimpang dari apa yang diharapkan DN Aidit yang membayangkan koperasi sebagai alat perjuangan kelas (1963). Spesifikasi lewat UU nomor 17/2012 ini pada dasarnya diambil dari spirit kapitalisme yang mengasumsikan bahwa spesifikasi dalam berbagai bidang akan meningkatkan produktivitas sebuah sistem, dalam hal ini koperasi; (3) Dengan dua argumen di atas, terma “kooperasi” yang diadopsi dari tulisan Mohammad Hatta (1954) terasa lebih pas tinimbang “koperasi”. Dan dengan adanya usaha penegakan kedaulatan pemilik yang sah SDA lewat pengambilan kebijakan peruntukannya yang dimungkinkan lewat rapat tahunan anggota kooperasi, maka tata kelola yang tersentral atau cuma menjadi bagian dari usaha dakwah dalam bentuk kongsi dagang (Jarkom Fatwa, 2004) dapat dihindari.
Kedua, kita dapat melihat argumentasi ideologis seperti yang ada dalam UUD ’45. UUD ’45 menyatakan bahwa seharusnya perekonomian negara dikelola dengan azas kekeluargaan, dalam hal ini kooperasi adalah bentuk yang paling memungkinkan. Kenyataannya, Pasca-Reformasi yang menguat justru korporasi. Dengan demikian, ini adalah momen untuk mengembalikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke khittah-nya dengan memberikan ruang pengelolaan SDA lewat kooperasi.
Ketiga, apakah mungkin mengelola bisnis besar di bidang SDA dengan struktur kooperasi? Hal ini bukan tanpa preseden. Kota Santa Cruz, Bolivia, yang memiliki 1,2 juta populasi, mengelola suplai air minum dengan pola kooperasi sejak tahun 1979, dan hingga saat ini merupakan salah satu penyedia air minum untuk publik yang terbaik di Amerika Latin. Semua pelanggan adalah anggota dari Cooverativa de Servicios Publicos Santa Cruz Ltda (SAGUAPAC) dimana para anggota memiliki hak untuk memilih pengurus kooperasi mereka. Tata kelola popular seperti ini sudah muncul di beberapa tempat lain seperti Kemitraan Publik di Ghana, dan Kemitraan Publik-Pekerja di Dhaka (Brennan, et al. 2004). Di Cochabamba dan La Paz/El Alto, Bolivia, pasca “Perang Air” awal tahun 2000-an, privatisasi sumber daya air ditolak kehadirannya di kedua kota dan memberikan alternatif berupa tata kelola Kemitraan Publik, meskipun masih menyimpan kelemahan di sana sini seperti efektivitas pelayanan dan pegawai yang tidak profesional (Spronk, 2007), kelemahan yang juga sangat mungkin dimiliki oleh sektor privat.
Pengarusutamaan tata kelola SDA oleh kooperasi adalah langkah awal yang perlu dilakukan di tingkatan Nahdliyin untuk mewujudkan kedaulatan di bidang SDA. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengkonsolidasikan berbagai elemen Nahdliyin yang sudah secara jelas menyatakan sikapnya seperti Pengurus Besar (PB) NU, PB PMII, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), dan FN-KSDA.
PB NU, pada 2012, melalui Konferensi Besar (Konbes) di Cirebon, di bidang ekonomi merekomendasikan “renegosiasi kontrak-kontrak karya pertambangan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi pemasukan Indonesia dan kesejahteraan warga” (PB NU, 2012). Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) malah memiliki tuntutan yang lebih tinggi. Pada tahun 2012 PMII menuntut dilakukannya nasionalisasi terhadap aset pertambangan dan energi (Anam, 2013 dan Rasyid, 2013). Sementara, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), menyatakan bahwa tujuan akhir dari tata kelola energi adalah kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Bahkan lebih jauh, ISNU mendukung dilaksanakannya reforma agraria (Syeirazi, 2013). FN-KSDA sendiri menetapkan “tata kelola SDA yang berkedaulatan dan sebesar-besarnya bermanfaat bagi rakyat Indonesia” sebagai tujuannya (FN-KSDA, 2013). Akan tetapi secara organisatoris, hampir tidak ada gelombang advokasi yang masif dari kelompok NU terhadap warga yang mengalami persoalan konflik SDA. PB NU sendiri lebih banyak bermain di level regulasi seperti judicial review UU Migas, tetapi tidak banyak mendorong pengurus untuk turun ke bawah.
Pola pengambilalihan perusahaan swasta seperti Palyja yang sedang dilakukan Jokowo-Ahok di DKI, mungkin tidak akan berarti banyak karena struktur negara di Indonesia yang masih predatoris, dimana negara lebih berposisi sebagai akumulator kapital yang menindas ketimbang distributor.
Kalau sukses di internal Nahdliyin, maka dalam konteks NKRI, tantangan berikutnya adalah menaikkan yang “parsial” ini menjadi sesuatu yang “universal”, persisnya menggalang aliansi dengan berbagai kelompok ideologi yang lain seperti nasionalis agar kelompok santri tidak bekerja sendiri dalam upayanya menerjemahkan ajaran-ajaran Gus Dur menegakkan kedaulatan di bidang tata kelola SDA.
Sebaliknya, bagi kelompok nasionalis, pengalaman kehilangan artikulasi pasca tahun 1998, dimana terjadi banyak privatisasi perusahaan negara justru di bawah Megawati Soekarnoputri, harus dijadikan pelajaran agar tidak terjebak kembali dalam permasalahan yang sama: ketidaksiapan ideologis dalam mengelola kekuasaan.
Akhirnya, menguatnya artikulasi ideologi nasionalis belakangan ini yang sebenarnya bagus, sekaligus mengundang kekhawatiran. Kemunculan pemimpin populis seperti Jokowi tidak akan membawa Indonesia kemana-mana tanpa disokong oleh konsolidasi ideologi dan pengorganisasian politik yang solid di belakangnya. Dan, setidaknya sampai sekarang, itulah yang terjadi.
———–
Penulis : Bosman Batubara
Sumber : gusdurian.net